In The Name of Identity menyorot bagaimana, dalam banyak peristiwa di zaman modern, kekerasan seringkali berakar dari konsepsi kita yang keliru dalam memaknai “identitas”. Dapat beli di Kampung Buku Jogja 3, esai panjang Amin Maalouf ini merupakan bacaan pertamaku dalam topik identitas, dan, sampai postingan ini kutulis, masih jadi yang terbaik, bahkan lebih bagus dari Kekerasan dan identitas-nya peraih nobel Amartya Sen—lebih-lebih karena kalimat-kalimat Amin Maalouf di esai ini sememikat karya sastranya: cenderung panjang-panjang, tapi mudah diikuti, dan sering diakhiri dengan poin yang mengejutkan. Buku yang diterjemahkan Ronny Agustinus ini tidak hanya melandasi pemahamanku tentang “identitas”, tetapi juga menjadi buku yang pada masanya sangat sering kutengok ketika ingin mengingat esai bagus itu seperti apa. Di bawah ini adalah kutipan terpilih dari In The Name of Identity.
Kutipan Buku
- Identitas tidak bisa disekat-sekat. Anda tidak bisa memberlah-belahnya jadi separuh, sepertiga, atau seberapa pun segmen terpisah. (Hal.2)
- Orang cuma perlu menengok aneka macam konflik yang sedang dipertarungkan di seluruh dunia dewasa ini hanya untuk menyadari bahwa tak ada satu pun pertalian itu yang punya supremasi absolut. (Hal.13)
- Hidup adalah percipta keberbedaan. Tak ada reproduksi yang pernah identik. Semua individu tanpa kecuali memiliki identitas campuran. (Hal.20)
- Seringkali cara kita memandang orang lainlah yang mengurung mereka dalam pertalian-pertalian mereka sendiri yang tersempit. Dan cara kita memandang mereka jugalah yang bisa membebaskannya. (Hal.22)
Identitas tidaklah terberi sekali untuk selamanya: ia dibangun dan berubah-ubah sepanjang hayat seseorang.
(Hal.23)
- Yang paling utama dalam menentukan pertalian seseorang dengan suatu kelompok manapun adalah pengaruh orang lain: pengaruh orang-orang di sekitarnya -kerabat, rakyat senegeri, umat seagama-yang berusaha menjadikannya satu dengan mereka. (Hal.25)
- Orang kerap memandang diri mereka dalam pengertian pertaliannya yang mana yang paling diserang. (Hal.26)
- Kita cuma perlu meninjau peristiwa-peristiwa sekian tahun terakhir untuk melihat bahwa komunitas manusia manapun yang merasa dipermalukan atau cemas akan eksistensinya akan cenderung memproduksi pembunuh. (Hal.29)
- bila manusia dari segala negara, dari segala kondisi dan iman kepercayaan bisa begitu mudah berubah jadi penjagal, bila kaum fanatik segala jenis bisa dengan mudah berlagak sebagai pembela identitas, hal itu karena konsep “kesukuan” atas identitas yang masih merata di seantero dunia memfasilitasi distorsi macam ini. (Hal.29)
- pendapat yang mereduksi identitas menjadi satu pertalian tunggal-mendorong orang untuk mengambil sikap parsial, sektarian, intoleran, mendominasi, kadang bunuh diri, dan acap kali bahkan mengubah mereka menjadi pembunuh atau penyokong pembunuh. (Hal.31)
- bila mereka merasa “yang lain” menghadirkan ancaman bagi kelompok etnis, agama, atau bangsanya, segala yang mungkin mereka perbuat untuk menghalau bahaya tampak sepenuhnya sah bagi mereka. (Hal.32)
- Awalnya ia [identitas] mencerminkan aspirasi yang sangat lumrah, lalu sebelum kita tahu di mana kita gerangan ia sudah menjadi instrumen perang. Peralihan dari satu makna ke makna lainnya tak terasa, nyaris ilmiah, dan kadang kita semua hanyut bersamanya. Kita kutuk ketidakadilan, kita bela hak-hak kaum teraniaya-dan hari berikutnya kita dapati diri jadi sekongkol pembantaian. (Hal.33-34)
- Status migran itu sendiri adalah korban pertama dari gagasan “kesukuan” atas identitas. Bila cuma satu pertalian yang penting, bila pilihan benar-benar harus diambil, seorang migran mendapati dirinya terbelah dan terkoyak, dikutuk untuk mengkhianati entah negeri asalnya atau negeri angkatnya, dan jalan manapun yang ia tempuh, pengkhianatan itu akan terus membuatnya merasakan kegetiran dan kegeraman abadi. (Hal.39)
- Saya berkata pada satu pihak [imigran]: “Semakin kau mendalami budaya tuan rumahmu, semakin kau mampu mendalami budayamu sendiri”; lantas pada pihak satunya [tuan rumah]: “Semakin seorang imigran merasa budayanya dihormati, makin terbuka ia pada budaya negeri tuan rumahnya.” (Hal.42)
- Bila saya mempelajari bahasa orang lain tapi ia tidak menghargai bahasa saya, maka terus bicara dalam bahasanya berhenti menjadi bukti persahabatan dan mulai menjadi sikap pengabdian dan ketertundukan. (Hal.44)
- Ketika sesuatu yang patut dicela diperbuat atas nama doktrin macam apapun, hal ini tidak otomatis membuat doktrinnya itu sendiri salah, sekalipun ia tidak bisa dianggap sama sekali tidak terkait dengan perbuatan dimaksud. (Hal.50)
Teksnya tidak berubah; yang berubah adalah cara kita memandangnya. Teks mempengaruhi realitas hanya melalui medium pandangan kita terhadapnya, dan dalam setiap era mata terpaku pada frasa-frasa tertentu dan meluncur di atas frase-frase lain tanpa menangkapnya.
(Hal.51)
- Abad 20 telah mengajari kita bahwa tak ada doktrin yang serta merta menjadi tenaga pembebas dalam dirinya sendiri: mereka semua bisa diselewengkan atau salah arah. (Hal.53)
- Dunia Muslim, yang selama berabad-abad menjadi pemimpin dalam urusan toleransi, kini mendapati diri tertinggal di belakang. (Hal.61)
- Tampak bagi saya bahwa pengaruh agama pada orang kerap dilebih-lebihkan, sementara pengaruh orang pada agama diabaikan. (Hal.62)
masyarakat senantiasa menghasilkan sebuah agama menurut gambarannya sendiri. Kendati demikian gambaran ini tidak pernah sama dari satu masa ke masa lainnya, begitu pun dari satu negara ke negara lainnya.
(Hal.64)
- Gerakan-gerakan ini [terorisme fanatis] bukanlah produk sejarah islam; mereka produk zaman kita dengan segala ketegangan, distorsi, tipu muslihat, dan keputusasaannya. (Hal.66-67)
- Anda boleh membaca selusin kitab tebal-tebal ihwal sejarah Islam dari sejak awal mulanya, dan Anda masih belum bisa memahami apa yang sedang berlangsung di Aljazair. Tapi bacalah 30 halaman soal kolonialisme dan dekolonialisasi, maka Anda bisa paham cukup banyak. (Hal.67-68)
Masyarakat membentuk agama, dan sebaliknya agama pada gilirannya membentuk masyarakat.
(Hal.69)
- Di manapun di planet ini seseorang kebetulan tinggal, semua modernisasi kini adalah westernisasi. Dan tren ini ditonjolkan dan dipercepat belaka oleh kemajuan teknis. (Hal.73)
- Meski kadang kala ia direngkuh dengan antusias, moderniasasi tak pernah diadopsi tanpa kegetiran tertentu, tanpa rasa dipermalukan dan kekalahan. Tanpa keraguan yang menikam tentang bahaya asimilasi. Tanpa krisis identitas yang mendalam. (Hal.74)
- Agar perubahan bisa diterima tidak cukup bila ia hanya sesuai dengan semangat zaman. Ia juga harus lolos ujian pada tataran simbolik, tanpa membuat orang-orang yang diminta berubah merasa mereka sedang mengkhianati dirinya sendiri. (Hal.75)
- Bukankah tugas pertama nasionalisme adalah mencari kambing hitam dalam tiap masalah, bukan solusinya? (Hal.82-83)
- peran menentukan dalam perkembangannya [fanatisme beragama] dimainkan oleh surut dan ambruknya dunia komunis. Lebih dari seabad sudah sejak Marxisme berjanji mendirikan masyarakat dunia baru di mana gagasan Tuhan akan sirna. Kegagalan proyek yang bukan cuma tataran ekonomi-politik ini, melainkan juga moral dan intelektual, membuahkan rehabilitasi kepercayaan yang hendak dienyahkannya ke keranjang sampah sejarah oleh Marxisme sendiri. (Hal.90)
“Manusia lebih merupakan anak zamannya ketimbang anak bapaknya”, tulis sejarawan Marc Bloch.
(Hal.103)
- masing-masing kita punya dua warisan: warisan vertikal yang menurun ke kita dari leluhur , komunitas religius, dan tradisi rakyat kita, serta warisan “horisontal” yang ditularkan ke kita oleh rekan semasa dan zaman kita hidup. (Hal.104)
- Banjir kata dan gambar tidak senantiasa menyuburkan semangat kritisisme. (Hal.114)
[salah satu] kegelisahan yang timbul akibat globalisasi: standarisasi bukan lewat mediokritas, melainkan hegemoni.
(Hal.115)
- Di antara semua pertalian kita yang bisa dikenali, bahasa nyaris selalu menjadi yang paling berpengaruh: hampir seberpengaruh agama, yang dalam satu pengertian telah menjadi pesaing utamanya sepanjang sejarah, meski kadang juga menjadi sekutunya. (Hal.133)
- tidak susah untuk membuktikan seseorang bisa hidup tanpa agama, jelas ia tidak bisa hidup tanpa bahasa. (Hal.133-134)
- Seandaipun ia bahasa inggris memenuhi secara lengkap sebagian kebutuhan kita saat ini, ada lain-lain lagi yang tidak dipuaskannya, khususnya: kebutuhan akan identitas. (Hal.139)
- zaman sekarang tiap orang jelas butuh tiga bahasa. Yang pertama adalah bahasa identitasnya; yang kedua adalah Inggris. Antara keduanya kita harus menganjurkan bahasa ketiga yang dipilih secara bebas, yang kerap namun tidak selalu bahasa Eropa lainnya (Hal.141-142)
- Selalu menjadi cacat serius untuk tidak mengenal bahasa Inggris, tapi kian lama juga kian jadi cacat serius untuk hanya mengenal bahasa Inggris saja. Dan ini juga berlaku sama bagi mereka yang memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa-ibunya. (Hal.142)
Sekularisme tanpa demokrasi adalah bencana bagi demokrasi dan sekularisme itu sendiri.
(Hal.148)
- Hukum mayoritas tidak senantiasa sinonim dengan demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan. Kadang ia bersinonim dengan tirani, perbudakan, dan diskriminasi. (Hal.153)
- Peristiwa-peristiwa di pelbagai negara dalam beberapa tahun berselang harus mengajari kita untuk berhati-hati manakala sebuah gagasan yang dipandang universal dipaksa melayani sebuah konflik identitas. (Hal.154)
- Pemilu tidak lebih tidak kurang mencerminkan gambaran yang dipunyai suatu masyarakat terhadap diri dan komponen-komponen sendiri. Mereka bisa membantu menghasilkan diagnosa, tapi mereka sendiri tidak pernah bisa menghasilkan obatnya. (Hal.156)
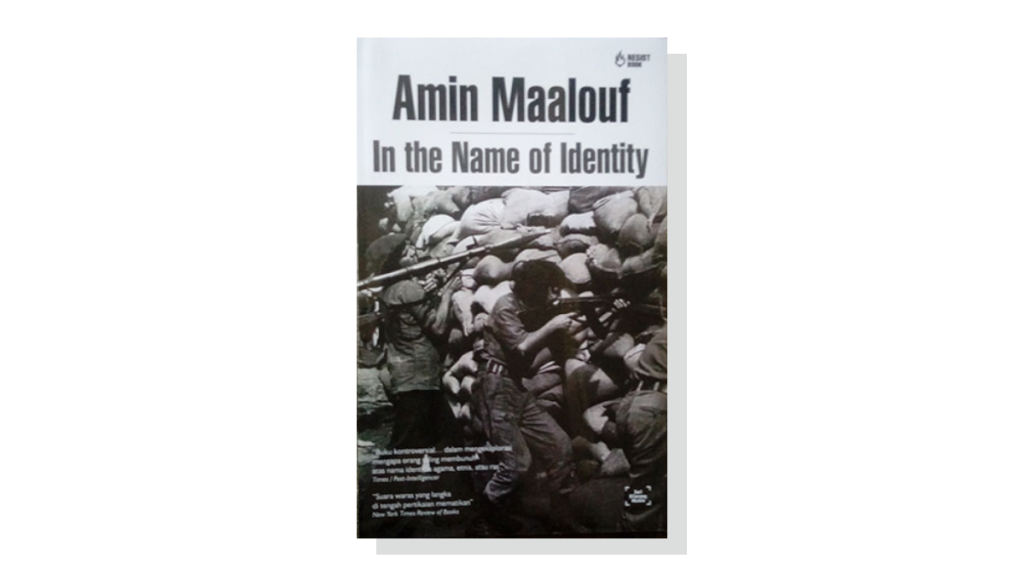
Bro.. komennya bro Щ(º_ºщ) #pengemiskomen